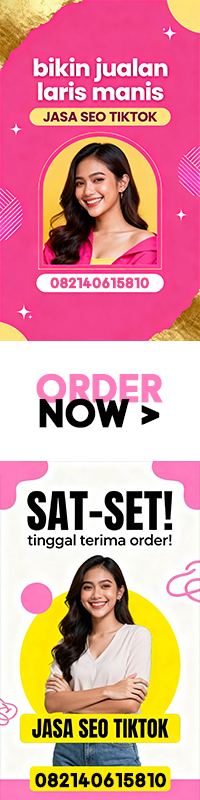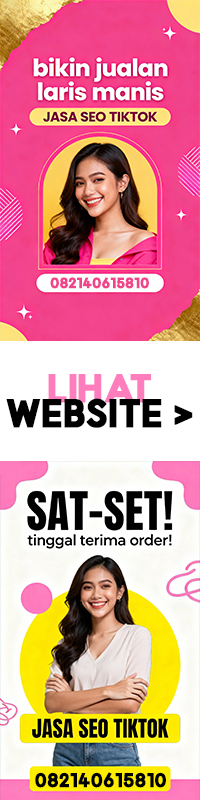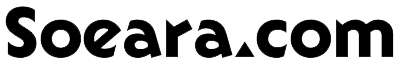Kantor agensi iklan di Jakarta Selatan kini tengah dihantam fenomena yang disebut “quiet quitting”. Banyak karyawan mulai menunjukkan sikap pasif dalam bekerja, hanya melakukan tugas sesuai batas jam kerja tanpa usaha ekstra. Fenomena ini memicu kekhawatiran bagi bos dan manajemen karena berpotensi mengurangi produktivitas perusahaan.
Kronologi Lengkap
Fenomena “quiet quitting” awalnya muncul sebagai respons terhadap tekanan kerja yang berlebihan, khususnya setelah pandemi. Banyak pekerja merasa lelah dengan beban kerja yang tidak seimbang dan kurangnya apresiasi dari atasan. Di Jakarta Selatan, khususnya di kantor agensi iklan, banyak karyawan mulai membatasi kontribusi mereka hanya pada tugas wajib, tanpa lagi mencoba memberikan inisiatif atau kerja tambahan.
Beberapa karyawan mengungkapkan bahwa mereka tidak lagi tertarik untuk bekerja lebih keras jika tidak ada kompensasi yang layak. Mereka ingin memiliki waktu lebih untuk kehidupan pribadi dan keluarga. Hal ini memicu perubahan pola kerja yang secara diam-diam mengubah dinamika di dalam perusahaan.

Mengapa Menjadi Viral?
Fenomena “quiet quitting” viral karena banyak orang mulai menyadari pentingnya keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Media sosial menjadi wadah utama penyebaran informasi tentang hal ini, terutama melalui video dan postingan yang menyoroti pengalaman nyata karyawan. Banyak netizen mulai memahami bahwa “quiet quitting” bukanlah tindakan malas, tapi upaya untuk menjaga kesehatan mental dan emosional.
Selain itu, isu ini juga menarik perhatian karena banyak perusahaan di Jakarta Selatan, termasuk agensi iklan, dikenal dengan budaya kerja yang sangat intensif. Dengan adanya “quiet quitting”, para karyawan mulai menolak untuk terjebak dalam lingkungan kerja yang tidak sehat.

Respons & Dampak
Banyak bos dan manajer agensi iklan di Jakarta Selatan merasa khawatir dengan dampak “quiet quitting”. Mereka mengkhawatirkan penurunan kualitas kerja dan kurangnya inisiatif dari karyawan. Beberapa perusahaan mulai mencari solusi, seperti meningkatkan komunikasi dengan karyawan dan memberikan insentif yang lebih baik.
Namun, beberapa ahli psikologi menilai bahwa “quiet quitting” bisa menjadi cara untuk menjaga kesehatan mental karyawan. Jika dikelola dengan baik, fenomena ini bisa membantu karyawan tetap produktif tanpa terbebani oleh tekanan berlebihan.

Fakta Tambahan / Klarifikasi
Menurut Audi Lumbantoruan, praktisi SDM, “quiet quitting” sebenarnya bisa jadi tanda adanya masalah dalam hubungan antara karyawan dan atasan. Ia menyarankan agar perusahaan lebih transparan dalam komunikasi, terutama soal gaji dan bonus. Menurutnya, kenaikan gaji harus dilakukan sesuai regulasi pemerintah, meskipun jumlahnya kecil.
Ia juga menegaskan bahwa bonus bukanlah kewajiban, tapi tergantung pada kondisi perusahaan. Namun, jika perusahaan tidak mampu memberi bonus, mereka harus berkomunikasi secara jujur dengan karyawan.

Penutup – Kesimpulan & Perkembangan Selanjutnya
Fenomena “quiet quitting” semakin mengguncang dunia kerja, terutama di kantor agensi iklan di Jakarta Selatan. Meski ada kekhawatiran dari bos dan manajemen, banyak karyawan merasa perlu menetapkan batasan untuk menjaga kesehatan mental. Publik kini menantikan bagaimana perusahaan akan merespons fenomena ini dan apa langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga keseimbangan antara produktivitas dan kesejahteraan karyawan.