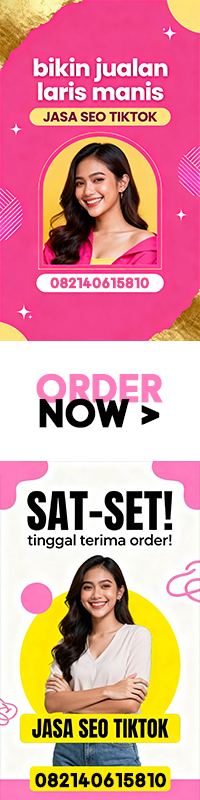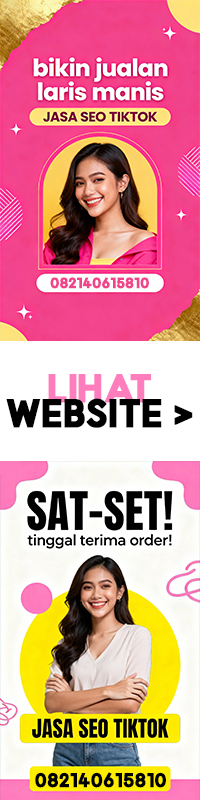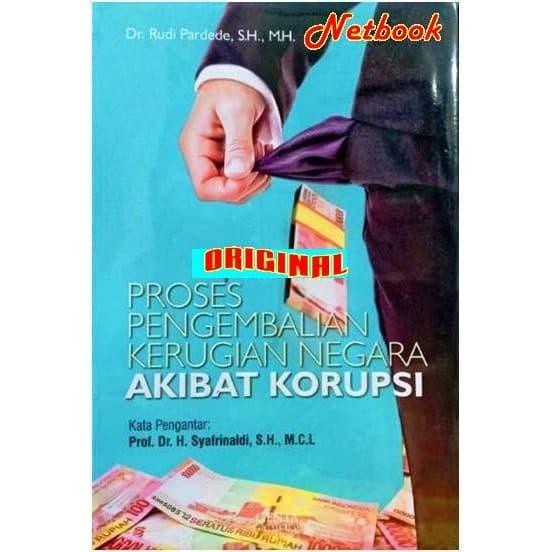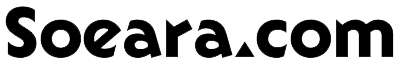Jakarta, Kompas.com – Kasus rehabilitasi yang diberikan oleh Presiden Prabowo Subianto kepada mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi, memicu perdebatan terkait kewenangan presiden dalam menentukan nasib para terpidana. Sejumlah pakar hukum tata negara mengungkapkan pandangan mereka mengenai batasan dan implikasi dari kebijakan ini.
Chairul Huda, pakar hukum pidana dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, menjelaskan bahwa rehabilitasi tidak secara otomatis menghapus vonis pidana yang telah dijatuhkan pengadilan. “Rehabilitasi hanya bersifat memulihkan martabat seseorang, bukan membatalkan putusan hukum,” ujarnya saat dihubungi.
Menurut Chairul, rehabilitasi pada dasarnya adalah upaya untuk mengembalikan hak-hak sipil atau kepegawaian seseorang. Namun, aspek pemidanaan tetap harus dijalankan. “Tanpa instruksi khusus dalam Keppres, pidana tetap harus dilaksanakan,” tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa proses hukum masih bisa ditempuh melalui banding atau peninjauan kembali (PK) agar vonis dapat digugurkan. “Nanti Keppres rehabilitasi itu jadi dasar dalam memori banding,” katanya.

Chairul mencontohkan kasus dua guru di Sulawesi Selatan yang mendapat rehabilitasi, namun tetap harus menempuh PK agar pidana yang telah dijalani dapat dihapus. Dalam kasus ASDP, ia menilai jalannya hukum juga serupa, yakni upaya hukum harus tetap ditempuh agar vonis dapat digugurkan.
Dia juga menyatakan bahwa penggunaan rehabilitasi bukanlah langkah ideal. “Kalau pendapat pribadi saya, agak tanggung presiden menggunakan rehabilitasi. Mestinya abolisi seperti Tom Lembong, kan perkaranya mirip,” ujarnya.
Kritik terhadap kebijakan rehabilistasi juga datang dari lembaga antirasuah seperti Indonesia Corruption Watch (ICW). Menurut Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, pemberian rehabilitasi merupakan bentuk intervensi eksekutif terhadap proses peradilan yang berpotensi mencederai independensi peradilan dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
“Presiden memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menggunakan hak-hak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi, dan abolisi tanpa ada garis batasan yang jelas,” kata Wana.
IM57+ Institute juga menilai keputusan Presiden memberikan rehabilitasi terhadap terpidana kasus ASDP menunjukkan pola intervensi yang kembali melemahkan kerja pemberantasan korupsi. Ketua IM57+ Institute, Lakso Anindito, menyatakan bahwa langkah tersebut menegasikan kerja keras penyidik dan penuntut KPK yang telah menangani perkara itu selama bertahun-tahun.
“Setelah Hasto mendapatkan amnesti pasca proses penyelidikan dan penyidikan panjang oleh KPK, kini rehabilitasi pada kasus ASDP menunjukkan Presiden tidak melihat secara substansial persoalan yang muncul dari fakta persidangan,” kata Lakso.
Selain itu, Fahri Bachmid, ahli hukum tata negara dari Universitas Muslim Indonesia, menyoroti pentingnya menjaga independensi peradilan. Ia menjelaskan bahwa membawa atribut ke dalam gedung pengadilan merupakan tindakan yang melanggar hukum.
“Fahri menjelaskan, penyampaian pendapat di muka umum merupakan hak setiap warga negara yang dapat diekspresikan melalui unjuk rasa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Namun, kegiatan tersebut harus dilakukan di tempat umum yang telah ditentukan, bukan di dalam gedung pengadilan atau ruang sidang,” ujar Fahri.
[IMAGE: Rehabilitasi presiden hukum tata negara]
Fahri juga menjelaskan bahwa kegiatan seperti menempelkan spanduk atau melakukan tindakan agitasi di dalam ruang sidang dapat mengganggu jalannya persidangan dan dianggap sebagai contempt of court. “Artinya setiap orang yang melakukan tindakan yang merendahkan, melecehkan, atau mengganggu wibawa pengadilan dapat dianggap melakukan contempt of court dan mempunyai konsekuensi pidana,” kata dia.
Dari segi hukum, tindakan tersebut diatur dalam Pasal 207 serta Pasal 217 hingga 223 KUHP, Pasal 28 dan 29 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung (Perma), serta Pasal 218 KUHAP yang mengatur kewajiban bersikap hormat di persidangan.
[IMAGE: Rehabilitasi presiden hukum tata negara]