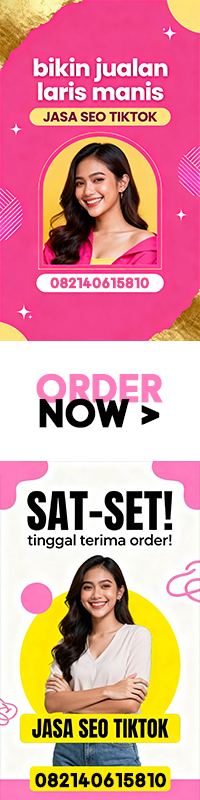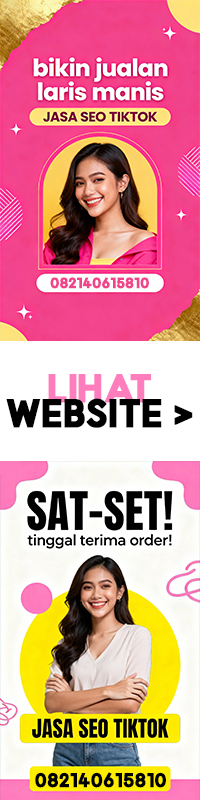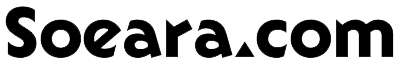Muhammad Yuzan Wardhana, Mahasiswa Doktoral Ilmu Pertanian Universitas Syiah Kuala
ACEHDikenal sebagai Serambi Mekkah, wilayah ini kaya akan budaya, sejarah, serta keindahan alam. Namun dalam dua puluh tahun terakhir, provinsi ini juga dikenal sebagai daerah yang rentan menghadapi bencana. Banjir bandang, tanah longsor, kebakaran hutan, hingga masalah krisis air bersih sering kali menjadi ancaman yang muncul setiap tahun. Bencana bukanlah sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ia merupakan hasil dari akumulasi kebijakan, tindakan manusia, dan perubahan ekologi yang tidak dikelola dengan baik.
Aceh saat ini berada di tengah perpecahan: antara mempertahankan warisan ekologisnya atau terus terjebak dalam siklus bencana yang semakin rumit. Artikel ini berusaha meninjau secara kritis akar masalah mulai dari kebijakan pertambangan, penebangan hutan ilegal, hingga perubahan fungsi hutan serta memberikan solusi revitalisasi yang realistis namun tegas.
Setiap tahun, bencana hidrometeorologi di Aceh semakin meningkat. Data dari BPBA menunjukkan peningkatan frekuensi banjir dan tanah longsor, khususnya di wilayah Aceh Tengah, Bener Meriah, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, serta beberapa kabupaten di pesisir timur dan barat. Namun, pertanyaan pentingnya adalah apakah ini murni bencana alam? Jawabannya tidak.
Sebagian besar bencana ini muncul sebagai akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi secara berkelanjutan. Hutan lindung yang selama ini berperan sebagai penyangga air mengalami penurunan kualitas yang cukup parah. Perubahan penggunaan lahan untuk perkebunan, kegiatan pertambangan, serta penebangan liar telah melemahkan kemampuan ekologis Aceh. Masalahnya tidak hanya terletak pada besarnya kerusakan, tetapi juga pada kedalaman akar kebijakan dan kurangnya pelaksanaan peraturan.
Tambang sering ditawarkan sebagai solusi ekonomi jangka pendek: menghasilkan pekerjaan dan pendapatan daerah. Namun di Aceh, peningkatan izin tambang justru menunjukkan sisi lain. Konflik sosial, pengendapan sungai, pencemaran air, serta kehilangan mata pencaharian masyarakat adat. Banyak area tambang terletak di hulu DAS (Daerah Aliran Sungai).
Ketika hutan dibuka untuk pertambangan, tanah menjadi gundul dan rentan terkikis, menyebabkan banjir besar saat musim hujan. Endapan memenuhi sungai-sungai di Aceh, sehingga kemampuan menampung air berkurang secara signifikan. Pertambangan ilegal memperburuk kondisi tersebut. Mereka beroperasi tanpa aturan lingkungan, tanpa AMDAL yang sah, dan tanpa proses pemulihan setelah operasi. Pada titik ini, kerusakan yang terjadi tidak hanya bersifat ekologis, tetapi juga etis dan institusional.
Kejahatan ekologis
Penebangan hutan secara ilegal (illegal logging) telah terjadi di Aceh sejak lama. Tujuannya beragam, mulai dari kebutuhan ekonomi masyarakat, perusahaan, hingga kelompok mafia kayu yang memiliki jaringan kuat. Meskipun pelakunya berbeda-beda, dampaknya selalu sama. Kehilangan tutupan hutan yang berfungsi sebagai penghalang alami. Hutan Aceh menjadi tempat tinggal bagi berbagai satwa penting seperti gajah, harimau, orang utan, dan badak Sumatera.
Saat hutan berkurang, tidak hanya mengakibatkan bencana lingkungan, tetapi juga meningkatkan perselisihan antara satwa dan manusia. Gajah datang ke kebun penduduk bukan karena mereka ingin mengganggu manusia, melainkan karena tempat tinggal mereka telah diambil alih. Ironisnya, penegakan hukum sering kali tidak mampu memberikan efek jera. Pelaku kecil ditangkap, namun jaringan besar tetap beroperasi. Masyarakat biasa sering menjadi korban, sementara para mafia kayu yang sebenarnya berada di balik layar, bahkan sempat terungkap beberapa waktu lalu bahwa seorang mantan tahanan kasus penebangan liar sedang bermain domino bersama Menteri Kehutanan RI, sebuah fakta yang menyedihkan.
Pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tanaman produktif lainnya merupakan isu lama yang sering terjadi di Aceh. Pada berbagai situasi, pengalihan ini dilakukan tanpa kejelasan dan tidak memperhatikan kemampuan lingkungan untuk menopangnya. Akibatnya, ketika kawasan hutan berubah menjadi lahan monokultur, muncul beberapa dampak signifikan.
Pertama, keanekaragaman hayati dan lanskap menjadi seragam. Kedua, menurunnya kemampuan tanah menyerap air akibat penggantian pohon kayu keras dengan tanaman industri berakar dangkal. Ketiga, meningkatnya suhu lokal wilayah. Dan keempat, terbentuknya kantong-kantong kerentanan sosial dan ekologis. Sebagai catatan penting, tanpa pengawasan tata ruang yang ketat, Aceh akan terus terjebak dalam siklus kerusakan. Pernahkah kita merenungkan, mengapa kerusakan ini terus terulang?
Banyak faktor utama yang menjadi penyebabnya, yaitu penegakan hukum yang lemah, banyak aturan yang hanya ada dalam dokumen, namun pelaksanaannya tidak konsisten, serta adanya konflik kepentingan antara ekonomi dan politik. Sektor ekstraktif sering kali mendapatkan perlindungan dari pihak politik, kurangnya koordinasi kebijakan antar sektor (seperti kehutanan, energi, pertanian, dan perencanaan tata ruang yang berjalan sendiri-sendiri), serta keterbatasan partisipasi masyarakat adat dan lokal. Padahal mereka merupakan pengawas terbaik bagi hutan. Faktor terakhir adalah keterbatasan data dan pemantauan yang menggunakan teknologi. Akibatnya, pemahaman terhadap kondisi saat ini tidak akurat tanpa data real time, sehingga pengawasan menjadi terlambat.
Langkah revitalisasi
Aceh memerlukan tindakan cepat namun terencana. Pemulihan ekologis bukanlah pekerjaan yang selesai dalam satu tahun, tetapi membutuhkan komitmen jangka panjang. Oleh karena itu, langkah pertama yang perlu diambil adalah pemberlakuan moratorium tambang dan pemeriksaan menyeluruh. Dalam hal ini, pemerintah Aceh harus menerapkan moratorium izin baru di daerah rentan bencana, melakukan audit independen terhadap seluruh izin pertambangan, serta mencabut izin yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan. Audit tersebut harus bersifat transparan dan melibatkan akademisi serta masyarakat sipil.
Langkah kedua, sistem pengawasan hutan yang menggunakan teknologi. Aceh mampu menerapkan pemantauan harian melalui satelit seperti Global Forest Watch, penerbangan drone secara berkala, serta memberikan akses ke database pelaporan masyarakat melalui aplikasi. Dalam hal ini, teknologi dapat memutus jaringan mafia kayu dengan bukti digital yang kuat. Langkah ketiga, rehabilitasi Daerah Aliran Sungai secara menyeluruh, di mana program rehabilitasi hulu DAS harus menjadi fokus utama.
Ini mencakup penanaman kembali pohon-pohon lokal yang memiliki nilai ekologis tinggi, pembangunan zona hijau di sepanjang tepi sungai, serta pemulihan area yang rusak parah akibat pertambangan.
Dalam hal ini, tidak cukup hanya melakukan penanaman kembali (reboisasi), tetapi diperlukan rencana perawatan selama minimal 5 tahun dan berkelanjutan. Langkah keempat adalah pemberdayaan masyarakat adat dan gampong. Masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan hutan yang jauh lebih berkelanjutan. Model seperti hutan adat, perhutanan sosial, eco-village yang berbasis konservasi, dapat dikembangkan dengan bantuan pemerintah. Langkah kelima yaitu tata ruang yang bersifat ramah ekologi. Rencana tata ruang harus didasarkan pada studi risiko bencana, membatasi alih fungsi hutan, serta menciptakan insentif bagi pemilik lahan agar tetap menjaga tutupan vegetasi.
Langkah keenam mengenai transparansi dan kepemimpinan hijau. Para pemimpin daerah perlu menjadi “pembela” lingkungan. Kebijakan pemerintah harus berfokus pada keberlanjutan, bukan hanya keuntungan jangka pendek. Aceh dapat bangkit, jika berani memilih jalur yang sulit. Bencana yang menimpa Aceh bukanlah takdir semata. Ia merupakan pesan dari alam yang memaksa kita untuk merenung. Jika Aceh ingin keluar dari siklus krisis ekologis, diperlukan keberanian bersama untuk mengubah arah pembangunan yang ramah terhadap lingkungan.
Aceh telah beberapa kali bangkit dari luka yang besar, termasuk bencana tsunami tahun 2004. Kerusakan tersebut memberi pelajaran bahwa kehidupan dapat dimulai kembali melalui komitmen, kesadaran, dan solidaritas. Sekarang, tantangannya berbeda, namun intinya tetap sama: berani mengambil keputusan penting untuk masa depan generasi berikutnya.
Aceh bukan sekadar sebuah daerah secara geografis. Ia merupakan tempat tinggal bagi sejarah yang panjang, keyakinan, serta harapan. Melindungi alam Aceh berarti menjaga harga diri dan masa depan penduduknya.