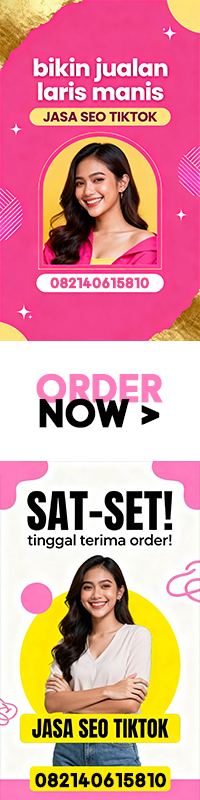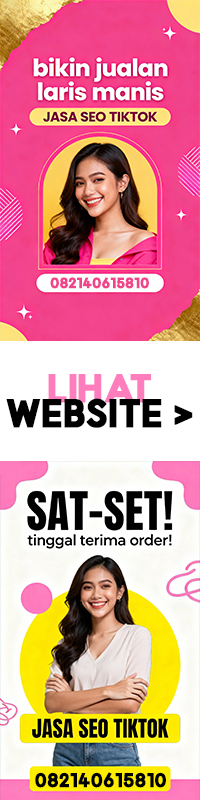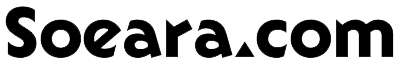Perubahan Iklim dan Tantangan Ketahanan Sosial di Indonesia
Di tengah perubahan iklim yang semakin nyata dampaknya, Indonesia berada pada persimpangan antara kerentanan ekologis dan ketahanan sosial yang terus diuji. Banjir yang datang lebih sering, musim kering yang lebih panjang, polusi udara yang kian memburuk, hingga hilangnya keanekaragaman hayati adalah tanda-tanda bahwa bencana ekologis bukan lagi ancaman masa depan melainkan realitas hari ini.
Namun, persoalan terbesar bukan semata-mata pada bencana alamnya, melainkan sejauh mana masyarakat mampu bertahan, beradaptasi, dan menjaga kohesi sosial ketika lingkungan yang menopang kehidupan mereka mengalami kerusakan hebat.
Sebab, pada akhirnya, permasalahan ekologis selalu berkaitan dengan aspek sosial. Saat hutan terbakar di Kalimantan dan Riau, bukan hanya pohon yang hilang—kesehatan masyarakat terganggu, habitat satwa terancam, akses pendidikan terganggu, roda ekonomi terhambat, dan komunikasi antarwarga pun berubah.
Ketika sebuah kota dilanda banjir besar, bukan hanya jalanan yang terendam—melainkan kepercayaan terhadap pemerintah diuji, solidaritas warga muncul atau memudar, dan kerentanan warga marjinal terlihat semakin jelas. Bencana ekologis adalah cermin atas struktur sosial kita: apakah kuat, rapuh, atau justru sedang runtuh perlahan.
Bencana ini bukan sekadar musibah alam, melainkan “akumulasi pelanggaran ekologis” akibat kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai (DAS), ditambah cuaca ekstrem yang semakin ganas karena perubahan iklim.
Di Sumatra, hujan ekstrem dipicu siklon tropis, tapi akar masalahnya adalah eksploitasi alam yang tidak berkelanjutan, seperti penebangan liar dan konversi lahan untuk perkebunan. Ini bukan bencana pertama; ingat gempa dan tsunami Palu 2018 atau erupsi Semeru 2021, yang semuanya memperlihatkan betapa rapuhnya ekosistem kita.
Ini adalah peringatan keras bagi kita bahwa bencana ekologis bukan hanya ancaman lingkungan, tapi juga ujian bagi ketahanan sosial. Bencana ekologis seperti ini acap kali terjadi di Indonesia. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan hingga September 2025, ada 2.461 kejadian bencana alam, dengan banjir sebagai yang terbanyak. Penyebab utamanya adalah deforestasi masif; pada 2024 saja, hilangnya hutan mencapai 261.575 hektare, yang memperburuk erosi tanah dan banjir.
Ketahanan Sosial
Ketahanan sosial adalah konsep yang menggambarkan kemampuan masyarakat untuk merespons krisis secara adaptif, bertahan, bangkit, lalu berkembang. Dalam konteks Indonesia, bibit-bibit ketahanan sosial selalu ada dalam kultur gotong royong, solidaritas, dan kemampuan masyarakat untuk berimprovisasi di tengah minimnya dukungan. Namun, kekuatan itu tidak bisa bekerja selamanya tanpa dukungan struktural. Ketahanan sosial, betapapun kuatnya, tidak bisa menggantikan peran negara dalam memitigasi bencana ekologis yang semakin kompleks.
Kita bisa melihatnya dari kasus banjir rutin. Warga di bantaran sungai mungkin sudah terbiasa mengangkat barang ke loteng saat air naik, saling membantu mengungsikan lansia, hingga memasak bersama di posko darurat. Namun, kebiasaan itu—meskipun penuh nilai solidaritas—tidak seharusnya menjadi normal.
Ketahanan sosial yang terlalu mengandalkan kemampuan warga justru berpotensi menjadi jebakan: pemerintah merasa masyarakat sudah “terlatih” menghadapi bencana, sehingga penanganan struktural sering tertunda. Padahal, adaptasi tanpa transformasi hanya memperpanjang derita.
Sebaliknya, ada contoh ketika ketahanan sosial didukung dengan baik oleh kebijakan ekologis. Misalnya, penguatan desa tangguh bencana di wilayah rawan tsunami, program rehabilitasi hutan mangrove yang melibatkan masyarakat pesisir, atau kampanye pengurangan sampah plastik yang dikawal oleh komunitas dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ketika dukungan kebijakan berjalan seiring dengan partisipasi masyarakat, ketahanan sosial berubah dari sekadar “bertahan hidup” menjadi “memperbaiki hidup.”
Masalah Kerusakan Ekologis
Masalahnya, kerusakan ekologis sering datang lebih cepat daripada respons kolektif kita. Perubahan tata ruang yang tidak terkontrol, deforestasi yang masih terjadi, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, hingga pembangunan yang kerap mengabaikan daya dukung lingkungan membuat masyarakat berada dalam posisi rentan.
Dalam situasi seperti ini, ketahanan sosial tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan beradaptasi secara pasif, tetapi harus dilihat sebagai kekuatan untuk mengorganisir diri, menyuarakan kepentingan ekologis, dan menuntut keadilan lingkungan.
Fenomena menarik: di banyak wilayah terdampak bencana, masyarakat menunjukkan solidaritas spontan yang luar biasa. Ketika gempa melanda, warga saling berbagi makanan; ketika banjir merendam pemukiman, internet dibanjiri informasi posko dan donasi; ketika polusi udara memburuk, komunitas berbagi masker gratis.
Solidaritas ini adalah harta sosial yang tidak dimiliki semua negara. Namun, solidaritas yang lahir dari krisis tidak bisa terus-menerus menjadi penopang utama. Ia harus dipelihara, diperkuat, dan dipadukan dengan mitigasi struktural agar mampu menghadapi bencana yang intensitasnya semakin tak terduga.
Di titik ini, kita harus mengakui bahwa bencana ekologis adalah sinyal keras bahwa cara kita membangun negeri harus berubah. Ekonomi tidak bisa terus berpegang pada eksploitasi alam; pembangunan tidak boleh mengorbankan keberlanjutan; dan kebijakan tidak bisa mengabaikan sains.
Lebih jauh lagi, ketahanan sosial harus diartikan bukan sekadar kemampuan warga untuk menolong warga lain, melainkan sebagai kemampuan kolektif untuk membangun sistem yang tangguh—mulai dari edukasi lingkungan, tata ruang yang adil, investasi energi bersih, hingga perlindungan ekosistem yang tersisa.
Bencana ekologi adalah cermin kegagalan kita menjaga harmoni dengan alam. Ketahanan sosial bukan hanya soal bertahan dari bencana, tetapi tentang transformasi mengubah apa yang selama ini dianggap normal: bahwa lingkungan adalah warisan kolektif, kuatkan komunitas, lindungi hutan, dan bangun masa depan yang tangguh. Hanya dengan begitu, Indonesia bisa bangkit menjadi bangsa yang resilien.