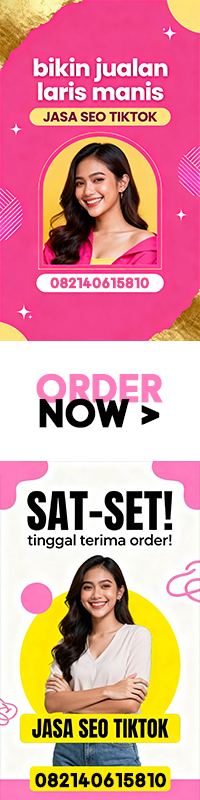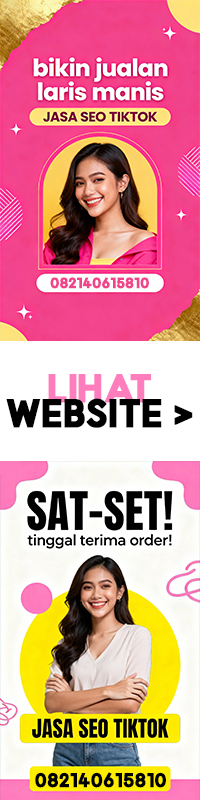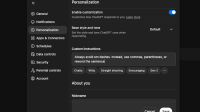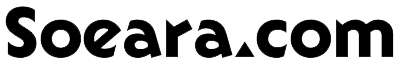Wati, yang diperankan oleh aktris Claresta Taufan, mengalami rasa sakit berulang saat perutnya dipijit demi mendapatkan keturunan. Sementara itu, suaminya sering marah saat diminta untuk memeriksa kesuburan ke dokter. Di dunia lain, Claresta memainkan peran Sartika yang harus bekerja di “kopi pangku” demi mencukupi kebutuhan anaknya sebagai ibu tunggal dengan dinamika hidup yang kompleks. Dua kisah perempuan ini muncul dalam film The Period of Her dan Pangku, yang tayang pertama kali pada tahun 2025. Kedua film tersebut ditayangkan dalam Jogja-Netpac Asian Film Festival yang berlangsung sejak 29 November hingga 6 Desember 2025.
Film tentang isu perempuan sering muncul dalam festival yang berusia 20 tahun ini. Ifa Isfanyah, Direktur JAFF, menyatakan bahwa festival memiliki fungsi untuk melihat kondisi dari perspektif yang beragam serta menjadi momen reflektif dari berbagai kejadian yang memantik kemanusiaan dan krisis. Ia menambahkan bahwa isu perempuan selalu mendapat tempat, termasuk juga bertumbuhnya para sutradara perempuan.

Praditha Blifa, salah satu sutradara yang terlibat dalam film The Period of Her, menyebut film sebagai media efektif untuk menyuarakan isu-isu inklusif tentang kelompok marginal, termasuk perempuan. Ia menjelaskan bahwa film bisa menyentuh titik empati manusia, sehingga saling terinspirasi dari karakter-karakter yang ada, baik di kota maupun daerah. Reza Rahadian, sutradara film Pangku, menilai bahwa isu perempuan tetap penting untuk disuarakan meskipun perkembangan teknologi telah pesat.
Loeloe Hendra Komara, sutradara film Tale of the Land, menyebut bahwa isu perempuan kini semakin terbuka dan tidak lagi dibatasi dalam penyampaiannya. Film barunya, A Life Full of Holes, yang bercerita tentang buruh migran perempuan, memperoleh tiga penghargaan pada JAFF Future Project tahun ini.

Sebelum Pangku, The Period of Her, dan Tale of The Land, Usmar Ismail pernah membuat film yang mengangkat isu perempuan berjudul Asrama Dara (1958), yang versi restorasi filmnya juga diputar di JAFF. Isu yang diangkat oleh Usmar berkaitan dengan stigma perempuan yang keluar tengah malam, cara berpakaian, persoalan jodoh, diskriminasi, hingga hubungan asmara. Berbagai isu terkait perempuan dalam film-film itu terdengar sama. Pertanyaannya, apakah situasi perempuan di Indonesia saat ini telah bertransfigurasi seperti tema JAFF tahun ini?
Direktur JAFF, Ifa Isfansyah, menyebut bahwa film yang diputar sepanjang perhelatan festival ini berdasarkan kurasi yang ketat. Dari hampir 900 film yang masuk, tim panel menyaringnya menjadi hanya 227 film—dari 43 negara. Mengacu pada jumlah film terpilih itu, sebanyak 60 sutradara perempuan lintas Asia terlibat di balik layarnya. Sutradara perempuan dari Indonesia tercatat 18 orang yang film diputar di JAFF 2025.

Menurut Ditha, mengangkat isu perempuan ke layar lebar terkadang menjadi beban bagi sutradara perempuan. Dua film pendek Ditha tentang perempuan, yaitu Kala Nanti (2024) dan Ngiring Belasungkawa (2019) lolos kurasi JAFF tahun 2021 dan 2024. Ia menyebut bahwa ada rasa takut dan kekhawatiran besar akan diterima atau dicekal. Film terbarunya, Romansa Keparat, yang menjadi bagian omnibus The Period of Her bersama tiga sutradara perempuan lain memupus kecemasannya. “Ternyata saat bersama ini makin terasa kuat ceritanya,” ujar Ditha.

Ideologi ibuisme yang dipropagandakan oleh Orde Baru telah diserap ke berbagai tingkat masyarakat, menurut sineas Dag Yngvesson, dalam sebuah diskusi panel di JAFF 2025. Akibatnya, kata Yngvesson, saat ingin menyuarakan pengalaman menghadapi ketidakadilan, perempuan harus menghadapi ketakutan dan kekhawatiran. Situasi ini disebutnya berpotensi menghambat kontribusi perempuan di berbagai bidang, termasuk film. Dalam bukunya berjudul Archipelagic Cinema: Screening Southeast Asian Modernity, Yngvesson menulis bagaimana pada masa lalu, para sutradara perempuan seperti Ratna Asmara, Sofia W.D, dan Roostijati menapaki jenjang dari aktris hingga kemudian menjadi sutradara.

Pengamat film, Fala Pratika, menilai budaya patriarki berpengaruh pada sudut pandang dalam bercerita mengenai perempuan. Ia menyatakan bahwa pada dekade-dekade sebelumnya, peran perempuan selalu disematkan antara sebagai istri atau sebagai ibu. Perempuan harus melekat pada entitas tertentu untuk menjadi perempuan. Namun belakangan, ia melihat penuturan pengalaman perempuan lewat layar lebar “semakin progresif” dan “memperlihat daya tanpa menginduk pada entitas tertentu”. Menurutnya, ini tak bisa dilepaskan dari jumlah perempuan dalam industri film yang terus bertumbuh—baik sebagai produser, sutradara, penulis skenario, penyunting gambar, hingga pengarah sinematografi.

Sutradara perempuan di Indonesia selama tahun 2010 hingga 2020 berjumlah 124 orang, menurut riset yang dikerjakan Sazkia Noor Anggraini, Rahayu Harjanthi, dan Tito Imanda, yang terbit dalam buku Menuju Kesetaraan Gender Perfilman Indonesia. Angka tersebut setara 11% dari total sutradara film di Indonesia. Loeloe Hendra Komara, yang juga menjadi pengajar di Jogja Film Academy, menyebut jumlah perempuan yang duduk di bangku sutradara saat ini terus bertambah. Meski tak bisa dipungkiri, kata dia, peningkatan jumlah tersebut tak sebanding dengan para lelaki yang menjadi sutradara.

Bisakah film Indonesia berkisah tentang perempuan tanpa ‘male gaze’? Reza Rahadian, aktor yang kini juga berkarier sebagai sutradara, menyebut dirinya menemukan berbagai isu perempuan saat menjalankan riset untuk filmnya yang berjudul Pangku. Pengalaman pribadinya sebagai anak yang diasuh oleh ibu tunggal juga turut masuk di dalam membangun cerita film tersebut. Ia mengakui, semula dia tidak memikirkan potensi masuknya sudut pandang pria (kerap disebut dengan istilah male gaze) ketika bertutur tentang sosok Sartika. Namun riset yang dilakukannya bersama tim membantu meningkatkan kesadaran terkait hal ini. “Betul, kreatornya laki-laki, penulis skenarionya laki-laki, tapi ketika kami membuat film ini, kami berusaha sejujur mungkin ini adalah tentang seorang perempuan yang sedang dihadapkan dengan persoalan kehidupan,” ujar Reza.