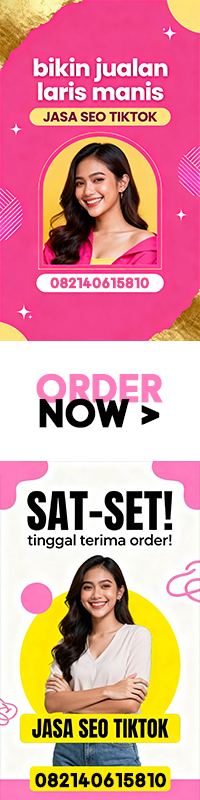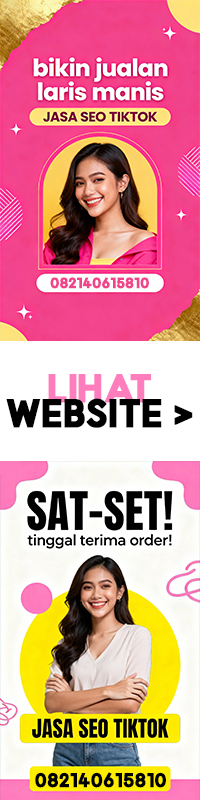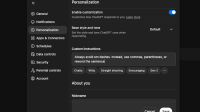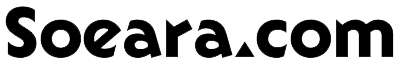Pemikiran Kritis tentang Redenominasi Rupiah
Pemerintah kembali menggulirkan rencana redenominasi rupiah. Dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2025–2029 (PMK 70/2025), penyusunan RUU Redenominasi ditargetkan rampung sekitar 2027. Ini bukan kali pertama wacana ini muncul, karena sebelumnya pernah diajukan pada 2013 tetapi mangkrak di DPR.
Di permukaan, narasi resmi terdengar mulus: efisiensi ekonomi, peningkatan daya saing, penguatan kredibilitas rupiah. Namun jika kita gali lebih dalam—baik dari sejarah rupiah maupun pengalaman negara lain—pertanyaannya menjadi jauh lebih tajam: ini reformasi serius, atau sekadar operasi kosmetik angka dengan biaya sosial dan fiskal yang tidak sedikit?
Apa Sebenarnya Redenominasi – dan Mengapa Pemerintah Ngotot?
Bank Indonesia sejak 2010 menegaskan bahwa redenominasi bukan sanering. Nilai riil dan daya beli tidak berubah; yang dihilangkan hanya beberapa digit nol, misalnya Rp1.000 menjadi Rp1, dengan harga barang ikut disesuaikan.
Artikel akademik dan kajian kampus (UI, Unesa) menguatkan definisi ini: redenominasi idealnya dilakukan ketika ekonomi stabil, inflasi rendah, dan sistem keuangan sehat, dengan tujuan utama menyederhanakan transaksi, akuntansi, dan sistem pembayaran, serta mempercantik citra mata uang di mata internasional.
PMK 70/2025 merangkum alasan pemerintah:
* efisiensi perekonomian dan peningkatan daya saing nasional,
* menjaga kesinambungan perkembangan perekonomian,
* menjaga nilai rupiah yang stabil dan daya beli,
* meningkatkan kredibilitas rupiah.
Di atas kertas, sulit menolak kalimat-kalimat seindah itu. Masalahnya: apakah kondisi dan institusi kita benar-benar siap menanggung konsekuensi teknis, politik, dan psikologis dari operasi ini?
Sejarah Wacana: Redenominasi yang “Hobi Mampir, Tak Pernah Menginap”
Redenominasi bukan wacana baru. Polanya berulang:
* Era SBY – Sekitar 2010 BI mulai mengkaji redenominasi; disebut perlu waktu 10 tahun dengan estimasi biaya hingga puluhan triliun rupiah untuk masa transisi panjang.
* Era Jokowi – RUU Redenominasi sempat masuk Prolegnas 2010-an awal; pemerintah sendiri mengakui implementasi butuh sekitar 11 tahun setelah RUU disahkan, sehingga tak mungkin dilakukan dalam satu periode pemerintahan.
* Era sekarang (pemerintahan Prabowo–Gibran) – RUU kembali dihidupkan, dimasukkan eksplisit sebagai tugas Kemenkeu dalam PMK 70/2025, dengan target selesai 2027.
Lembaga Kajian Keilmuan FHUI secara lugas menyebut: redenominasi di Indonesia “lebih tampak sebagai keinginan daripada kebutuhan”, dan mempertanyakan apakah manfaatnya cukup signifikan untuk membenarkan penggunaan dana publik yang tidak kecil.
Artinya, selama lebih dari satu dekade, redenominasi hidup sebagai wacana berbiaya tinggi yang terus diulang, tetapi tak pernah benar-benar masuk fase eksekusi. Ini sendiri sudah sinyal serius tentang betapa beratnya konsekuensi kebijakan ini—bahkan bagi pemerintah yang menggagasnya.
Argumen Pro: Efisiensi, Citra, dan “Elegansi Angka”
Tidak adil jika hanya melihat sisi gelap. Sejumlah studi dan analis menegaskan beberapa manfaat potensial:
* Efisiensi teknis: penulisan angka menjadi lebih pendek, memudahkan sistem pembayaran, akuntansi, pencatatan transaksi, dan operasi teknologi informasi (misalnya di bursa efek dan perbankan).
* Citra rupiah: rupiah saat ini, bersama dong Vietnam, dikenal sebagai mata uang “ber-nominal besar” di kawasan. Redenominasi dipandang bisa mengubah persepsi negatif soal “rupiah lembek”, meskipun secara teori nilai tukar riil tidak berubah.
* Konsistensi dengan praktik internasional: banyak negara berhasil meredenominasi: Turki (2005), Brasil (1994), Polandia (1995) dan beberapa negara Amerika Latin/Eropa Timur yang memangkas 3–6 nol setelah paket stabilisasi inflasi dan reformasi struktural.
Secara teoritis, ini bukan kebijakan “ngawur”. Tapi kapan dan di konteks apa kebijakan itu diambil akan menentukan hasil: menjadi alat modernisasi keuangan, atau hanya mengaduk-aduk angka di tengah struktur ekonomi yang rapuh.
Titik Rawan 1: Apakah Fondasi Kita Cukup Kokoh?
Penelitian-penelitian yang dikutip The Indonesian Institute dan berbagai jurnal ekonomi menyimpulkan hal yang sama: redenominasi cenderung berhasil ketika:
* inflasi rendah dan stabil,
* stabilitas politik relatif kuat,
* efektivitas dan integritas pemerintah tinggi.
Justru aspek terakhir yang dikritik tajam oleh The Indonesian Institute. Mereka menyoroti indeks integritas pemerintah Indonesia yang masih dikategorikan “repressed” dalam Indeks Kebebasan Ekonomi 2025, jauh di bawah Singapura. Ditambah lagi, koordinasi pusat–daerah yang lemah, korupsi, mismatch kebijakan, dan konflik kepentingan elite dianggap bisa menjadi bom waktu jika redenominasi dipaksakan.
Dengan kata lain, redenominasi adalah kebijakan berisiko tinggi yang menuntut pemerintah yang sangat kredibel dan sistem administrasi yang disiplin. Pertanyaannya: apakah kita sudah sampai di titik itu, atau justru masih bergulat dengan “PR lama” yang tak kunjung selesai?
Titik Rawan 2: Luka Sejarah Sanering dan Inflasi Psikologis
Secara teknis, BI dan akademisi sudah berkali-kali menjelaskan bahwa redenominasi bukan sanering. Redenominasi hanya menyederhanakan nominal; sanering memotong nilai uang dan daya beli.
Namun, masyarakat Indonesia punya memori pahit sanering 1960-an yang merontokkan nilai tabungan rakyat. Artikel Unesa mengingatkan bahwa tanpa sosialisasi massif, masyarakat rawan menyamakan dua hal ini, menimbulkan kepanikan, penimbunan, dan spekulasi harga.
Kajian hukum FHUI menegaskan kekhawatiran yang lebih tajam:
* rakyat kecil bisa dirugikan oleh lonjakan harga pangan akibat pedagang “ikut-ikutan bingung” atau justru memanfaatkan kebingungan,
* kebijakan yang ambigu dan multi-tafsir berpotensi melahirkan ketidakadilan baru bagi kelas menengah bawah.
Pengalaman negara lain menambah alarm: Zimbabwe melakukan redenominasi dalam situasi inflasi ekstrem; sepuluh digit nol dipotong, tetapi inflasi tetap melesat hingga level miliaran persen per bulan. Di sana, redenominasi justru mempercepat runtuhnya kepercayaan terhadap mata uang nasional.
Tanpa komunikasi publik yang jernih, jujur, dan panjang, redenominasi di Indonesia berpotensi memicu inflasi psikologis: harga dibulatkan naik, bukan turun—dan lagi-lagi yang paling babak belur adalah mereka yang penghasilannya pas-pasan.
Titik Rawan 3: Biaya Sistemik vs Prioritas Bangsa
BI pernah memperkirakan bahwa proses redenominasi yang ideal (dengan masa transisi panjang 10 tahun) memerlukan biaya hingga sekitar puluhan triliun rupiah secara nasional, untuk desain, pencetakan uang baru, penyesuaian sistem, hingga perubahan infrastruktur IT di sektor publik dan swasta.
Artikel kebijakan yang kritis menggambarkan redenominasi sebagai salah satu “rekayasa sistemik terkompleks” dalam sejarah keuangan Indonesia: seluruh sistem—mulai dari mesin EDC, software akuntansi, kontrak, papan harga, struk, hingga regulasi—harus disesuaikan serentak.
Pertanyaan yang tak nyaman, tapi wajib diajukan:
* Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperbaiki pendidikan, layanan kesehatan, infrastruktur dasar, dan transisi energi, apakah menghabiskan puluhan triliun untuk “merapikan nol” adalah prioritas yang bijak?
* Apalagi, sebagian manfaat teknis (misalnya kemudahan pencatatan dan efisiensi transaksi) sebenarnya bisa dikejar melalui digitalisasi sistem pembayaran, standarisasi sistem IT, dan pembenahan administrasi, tanpa harus mengganti angka di setiap lembar rupiah.
Titik Rawan 4: Simbolisme vs Reformasi Struktural
Ada satu risiko lain: politisasi dan simbolisme.
Redenominasi mudah dipasarkan sebagai “tonggak sejarah”, “babak baru rupiah”, atau “simbol Indonesia baru”. Padahal, akar persoalan ekonomi Indonesia jauh lebih dalam: basis pajak sempit, produktivitas stagnan, ketimpangan tinggi, dan kebocoran anggaran yang kronis.
Laporan-laporan kebijakan yang tajam mengingatkan bahwa redenominasi hanya akan bermakna jika:
* didahului reformasi fiskal dan moneter yang serius,
* diikuti penguatan integritas pemerintah,
* dan dipayungi komunikasi publik yang transparan.
Tanpa itu, redenominasi berisiko menjadi “kebijakan kosmetik”: rupiah tampak lebih “ganteng” di kertas, tetapi struktur ekonomi yang menopangnya tetap keropos.
Belajar Jujur dari Negara Lain
Studi komparatif menyebut:
* Turki, Brasil, Polandia – sukses setelah reformasi anti-inflasi keras, disiplin fiskal, dan penguatan institusi; redenominasi menjadi “penyegel” babak baru kebijakan, bukan titik awal reformasi.
* Zimbabwe, beberapa negara Afrika/Latin lain – gagal karena redenominasi dilakukan saat inflasi masih liar, kredibilitas pemerintah rendah, dan tidak ada paket kebijakan pendukung yang kredibel.
Indonesia berada di mana? Inflasi relatif moderat, tapi integritas pemerintahan dan efektivitas tata kelola masih jadi masalah besar menurut banyak indikator.
Artinya, kita berada di zona abu-abu: cukup stabil untuk mulai berpikir soal redenominasi, tetapi belum cukup kuat untuk menjalankannya tanpa risiko besar.
Penutup: Sebelum Menggunting Nol, Rapikan Dulu Fondasinya
Secara teoritis, redenominasi bukan kebijakan bodoh. Ia bisa menjadi alat modernisasi sistem keuangan dan simbol kedewasaan ekonomi. Tetapi dalam konteks Indonesia hari ini, ada beberapa kesimpulan tajam yang sulit diabaikan:
* Redenominasi adalah high-risk, medium-benefit.
* Manfaat utamanya lebih banyak di ranah teknis dan simbolik; risiko utamanya menyentuh kepercayaan publik, stabilitas harga, dan beban fiskal.
* Keberhasilan lebih ditentukan oleh kualitas institusi daripada kecanggihan desain uang baru.
* Selama integritas pemerintah, koordinasi pusat–daerah, dan penegakan hukum masih rapuh, redenominasi akan berjalan di atas tanah yang retak.
* Luka sejarah sanering dan potensi inflasi psikologis harus dianggap serius, bukan sekadar masalah “komunikasi”.
* Di negara dengan literasi keuangan rendah, salah langkah sosialisasi bisa mengubah kebijakan teknis menjadi krisis kepercayaan.
Maka, pertanyaan kuncinya bukan sekadar:
“Perlukah Indonesia redenominasi rupiah?”
Tetapi lebih tajam lagi:
“Berani kah pemerintah mengakui bahwa sebelum mengutak-atik nol di lembar rupiah, yang jauh lebih mendesak adalah merapikan nol-koma integritas dan kredibilitas kebijakan?”
Jika jawaban jujurnya belum, maka rencana redenominasi sebaiknya tetap berada di rak “opsi jangka panjang”—bukan dikebut demi mengejar “elegansi angka” sambil meninggalkan rakyat dalam kebingungan harga dan ketidakpastian baru.