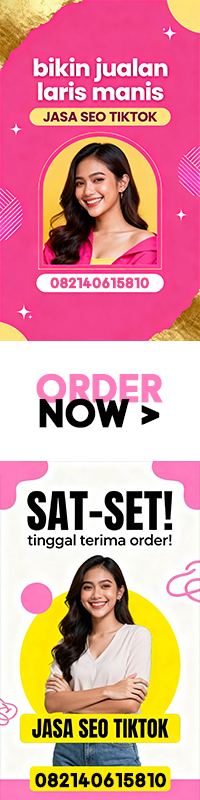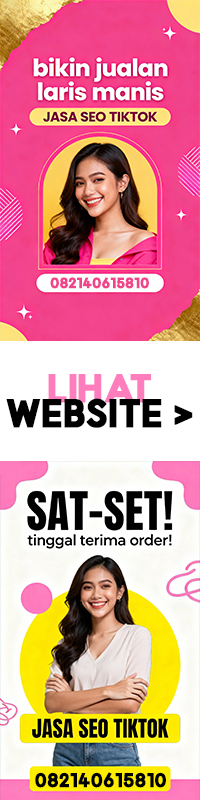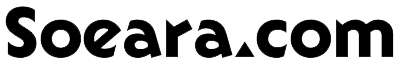Bencana Ekologis sebagai Kegagalan Sistemik
Banjir, banjir bandang, dan tanah longsor yang meluluhlantakkan Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat bukan sekadar “musibah alam”. Ia adalah hasil langsung dari kekuasaan yang korup, politik yang jual-beli, regulasi yang dimanipulasi, dan kerakusan oligarki yang bersekutu dengan partai politik serta pemerintah untuk mengeruk hutan atas nama investasi. Bila negara terus memerankan diri sebagai broker konsesi, bukan penjaga keselamatan warga, maka tragedi di Sumatera bukanlah puncak, tetapi pembuka pintu bagi deretan bencana di Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, NTT, Papua – semua wilayah yang telah dijual kepada tambang dan sawit. Inilah banjir besar oligarki, bukan semata banjir besar air hujan.
Akar Kerusakan
Bencana ekologis yang merenggut ratusan nyawa di Aceh-Sumut-Sumbar memperlihatkan apa yang sudah berkali-kali diingatkan para ekolog dunia: ketika hutan hilang, masyarakat kehilangan masa depan. Lynn White Jr. (1967) sudah lama memperingatkan bahwa krisis ekologis adalah krisis moral yang berakar pada cara manusia memandang alam sebagai objek dominasi. Namun di Indonesia, kerusakan ini bukan hanya soal worldview; ia adalah persoalan struktur kekuasaan yang menopang ekonomi ekstraktif.
Political ecologist seperti Peluso dan Watts (2017) menjelaskan bahwa bencana ekologis di negara berkembang tidak bisa dilepaskan dari relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat, di mana kebijakan publik dibentuk oleh kepentingan pemodal. Data terbaru Walhi, Greenpeace, dan Forest Watch Indonesia menunjukkan bahwa lebih dari 60 persen kawasan rawan longsor dan banjir besar justru berada dalam radius konsesi hutan dan tambang (FWI, 2023; Greenpeace, 2024). Ini bukan kebetulan. Ini pola.
Filsuf Hans Jonas (1984) dalam The Imperative of Responsibility menegaskan bahwa teknologi dan ekonomi modern menciptakan kekuatan destruktif yang mampu menghancurkan masa depan seluruh komunitas, sehingga etika baru harus memerintahkan: bertindaklah sehingga akibat tindakanmu tidak menghancurkan keberlanjutan kehidupan di muka bumi. Di Indonesia, prinsip Jonas ini diinjak-injak oleh kekuasaan politik. Kebijakan kehutanan bukan bergerak demi keselamatan warga, tetapi demi selamatnya modal.
Money Politics sebagai Fondasi Bencana
Setiap musim pemilu, uang mengalir. Setiap uang mengalir, hutan ditebang. Setiap hutan hilang, banjir bandang tiba. Siklusnya linear. Para ahli etika politik sebagaimana dicatat Thompson (2020) menyebut money politics sebagai “korupsi struktural” karena ia mengubah seluruh tujuan lembaga politik dari melayani publik menjadi melayani penyandang dana. Artinya, setiap suara yang dibeli hari ini, dibayar oleh rakyat dalam bentuk korban jiwa besok.
Konsesi tambang dan sawit yang merusak ekosistem tidak jatuh dari langit. Ia adalah balas jasa politik. Pemerintah pusat maupun daerah mengeluarkan izin dengan narasi investasi dan lapangan kerja. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya: konsesi memperkaya elite dan memiskinkan rakyat melalui bencana berulang. Di sinilah analisis filsuf Slavoj Žižek menjadi relevan. Žižek (2021) menulis bahwa kapitalisme kontemporer menciptakan “kekerasan sistemik,” yaitu kerusakan yang tidak tampak tetapi menghasilkan tragedi nyata yang dipersepsikan sebagai natural, padahal bersifat struktural. Banjir bandang Aceh-Sumut-Sumbar adalah kekerasan sistemik itu: kekerasan ekonomi yang terakumulasi menjadi kekerasan alam.
Alam yang Dipaksa Diam
Pandangan antropolog Tim Ingold (2011) sangat penting: alam bukan objek mati, melainkan “lingkungan hidup” yang berelasi dengan manusia dalam aliran timbal balik. Ketika relasi ini diputus secara sepihak oleh industri ekstraktif, alam tidak tinggal diam; ia merespons. Respons alam bukan moralistik, tetapi kausal: tebang hutan → hilang akar → hilang penahan → tanah longsor → air meluap → manusia mati.
Namun masyarakat sering disuguhi narasi bahwa ini adalah “bencana alam”, bukan bencana buatan manusia. Narasi ini adalah strategi pemutihan kesalahan negara. Filsuf lingkungan Val Plumwood (2002) menyebutnya sebagai denial of agency penyangkalan atas fakta bahwa manusia memiliki peran kausal dalam kerusakan alam. Penyangkalan ini memuluskan kelanjutan perusakan.
Moralitas yang Gagal
Secara etis, negara dan korporasi melanggar prinsip dasar etika lingkungan yang ditegaskan Holmes Rolston III (2012): bahwa alam memiliki nilai intrinsik, bukan sekadar nilai ekonomi. Ketika hutan direduksi menjadi komoditas, maka tindakan manusia kehilangan horizon moral. Etika publik juga runtuh. Pemerintah berkewajiban melindungi warga (obligasi konstitusional), namun justru menjadi agen perantara bagi modal yang mempercepat kerentanan warga. Di titik ini, negara telah gagal menjalankan fungsi teleologisnya.
Pakar etika lingkungan Aldo Leopold (1949) memformulasi land ethic: “A thing is right when it preserves the integrity, stability, and beauty of the biotic community.” Indonesia melakukan kebalikannya: mengambil keputusan politik yang merusak integritas ekosistem.
Trauma Kolektif
Dari sisi psikologi bencana, tragedi di Sumatera menorehkan collective trauma. Erikson (1976) menyebut trauma kolektif sebagai “pecahnya jaringan relasi sosial dan makna” yang dialami bersama. Rumah yang hilang bisa dibangun kembali, tetapi keterikatan identitas terhadap tanah, kampung, dan memori tidak bisa dipulihkan oleh bantuan sembako. Trauma ekologis bersifat jangka panjang: generasi muda tumbuh dalam rasa takut terhadap hujan; petani kehilangan tanah; anak-anak hidup dengan kecemasan setiap kali mendengar suara air besar. Di sinilah bencana ekologis berubah menjadi bencana psikososial.
Yang lebih mengerikan, trauma ini tidak diakui negara. Bantuan terbatas, perhatian sporadis, dan narasi media diringkas menjadi “banjir bandang kembali terjadi”. Bencana “kembali terjadi” karena diperbolehkan untuk kembali terjadi.
Keadilan yang Absen
Dari perspektif hukum, Indonesia sebenarnya memiliki kerangka regulasi memadai: UU Kehutanan, UU Lingkungan Hidup, UU Minerba, dan berbagai aturan turunannya. Namun problemnya bukan pada absennya hukum, melainkan absennya penegakan. Richard Stewart (2015) menggambarkan bahwa negara dengan governance lemah cenderung memperlakukan hukum sebagai “instrumen formal,” bukan alat perlindungan ekologis. Hukum menjadi ornamen, bukan instrumen.
Konsesi yang mestinya tunduk pada Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) sering disetujui melalui proses manipulatif. Banyak pakar hukum lingkungan mencatat bahwa Amdal di Indonesia sering menjadi “dokumen untuk memenuhi syarat administratif, bukan mekanisme perlindungan lingkungan” (Nurhasanah, 2024). Akibatnya, perusahaan melenggang tanpa pengawasan, pemerintah mendapat pemasukan, elite mendapat keuntungan, sementara rakyat menerima kuburan massal. Inilah bentuk ecological injustice, ketidakadilan ekologis: keuntungan dinikmati minoritas, tapi risiko ditanggung mayoritas.
Krisis Makna terhadap Alam
Krisis lingkungan di Indonesia tak bisa dilepaskan dari tesis Martin Heidegger tentang Gestell – bahwa teknologi modern memaksa manusia melihat alam hanya sebagai “standing reserve”, sumber daya yang tersedia untuk diekstraksi. Ketika alam dipahami sebagai gudang ekonomi, maka pertimbangan moral hilang. Filsuf Jerman lainnya, Jürgen Habermas, menawarkan jalan dengan practical discourse: keputusan harus dihasilkan melalui komunikasi rasional yang mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Tapi di Indonesia, diskursus digantikan lobi. Habermas tidak pernah membayangkan bahwa ruang publik bisa dibajak secara sistematis oleh oligarki.
Dalam etika Timur, ekofilosofi Jepang, misalnya, menekankan satoyama – keseimbangan harmonis manusia-alam. Fritjof Capra (2021) menyebut ini sebagai prinsip dasar ekologi sistem: kehidupan hanya mungkin ketika relasi yang saling menopang dijaga. Indonesia menghapus relasi itu dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang self-destructive.
Ketimpangan yang Mengalir Seperti Air Bah
Kerusakan ekologis memperparah ketimpangan sosial. Masyarakat miskin tidak memiliki bufer untuk menghadapi bencana. Mereka tinggal di tepi sungai karena tidak punya pilihan; mereka bertani di lereng curam karena tanah datar sudah dikuasai perkebunan besar. Dengan demikian, bencana ini bukan hanya tragedi alam, melainkan tragedi kelas. Para ahli sosiologi bencana seperti Anthony Oliver-Smith (2019) menyebut bahwa kerentanan sosial menentukan tingkat keparahan akibat bencana. Dan kerentanan sosial di Indonesia bukan bawaan, tetapi hasil kebijakan.
Ketika pemerintah memberikan ribuan bahkan jutaan hektar kepada perusahaan, masyarakat sekaligus dicabut haknya terhadap tanah dan hutan. Mereka kehilangan ruang hidup, sehingga ketika alam kehilangan daya dukungnya, mereka pula yang pertama mati.
Korelasi yang Tidak Bisa Dibantah
Setelah melihat kerangka filosofis, etis, sosial, antropologis, psikologis, dan yuridis, korelasi antara korupsi politik – termasuk money politics – dengan bencana ekologis menjadi sangat jelas:
Money politics → elite berutang pada oligarki → kebijakan lingkungan dilonggarkan → konsesi diberikan → hutan hilang → daya dukung runtuh → banjir bandang dan longsor terjadi → rakyat menjadi korban.
Inilah rantai sebab-akibat yang tidak bisa diputus oleh narasi “ini musibah” atau “ini kehendak alam.” Sebagaimana dinyatakan Paus Fransiskus dalam Laudato Si’ (2015), “Krisis ekologis adalah krisis politik dan moral.” Indonesia sedang mengalaminya secara telanjang.
Peringatan bagi Seluruh Indonesia: Sumatera Baru Pembuka
Aceh, Sumut, dan Sumbar adalah peringatan awal. Mereka adalah lonceng kematian yang mengetuk pintu seluruh negeri. Kalimantan telah kehilangan lebih dari 50 persen tutupan hutan aslinya; beribu lubang tambang menganga seperti jebakan maut. Kalimantan Selatan telah dilanda banjir besar berulang. Kalimantan Timur, sebagai calon ibu kota negara, berdiri di atas tanah rapuh yang sudah ditambang puluhan tahun.
Sulawesi menanggung risiko tinggi akibat tambang nikel. Maluku, Maluku Utara dan Papua menanggung beban kekerasan ekologis yang dipaksakan. NTT yang kering pun mulai retak karena alih fungsi lahan dan pembangunan yang tidak memikirkan daya dukung. Jika Sumatera menjadi awal, maka Indonesia Timur akan menjadi kelanjutannya, dan Jawa yang penuh sesak akan menerima giliran dari kerusakan hulu sampai hilir.
Setiap daerah yang memiliki konsesi tambang dan sawit adalah seperti bom ekologis dengan sumbu waktu. Pertanyaannya bukan apakah bom itu akan meledak – tetapi kapan.
Membangun Ulang Relasi Manusia-Alam
Jika krisis ini bersifat moral, maka penyelesaiannya juga harus dimulai dari moral. Hans Jonas memerintahkan tanggung jawab radikal terhadap generasi mendatang. Leopold menuntut kita memasukkan alam ke dalam komunitas moral. Plumwood menekankan relasi timbal balik. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip itu berarti: menghentikan politik uang dalam pemilu; memutus hubungan parasit antara elite politik dan oligarki; memulihkan hutan dan DAS; menegakkan hukum lingkungan tanpa kompromi; menempatkan keselamatan masyarakat di atas bisnis.
Etika tanpa kebijakan hanyalah khotbah kosong. Tetapi kebijakan tanpa etika adalah mesin perusak. Negara harus memilih: menjadi pelindung kehidupan, atau agen bencana.
Agar Air Tak Lagi Menjadi Kuburan
Bencana Aceh-Sumut-Sumbar membuka kebenaran pahit: Indonesia sedang kehilangan masa depan ekologisnya. Kerusakan ini bukan takdir, tidak natural, dan bukan konsekuensi tunggal perubahan iklim. Ia adalah produk politik yang korup, ekonomi yang tamak, dan negara yang gagal menegakkan keadilan ekologis. Para filsuf, ekolog, antropolog, dan ahli psikologi telah mengingatkan bahwa hubungan manusia–alam tidak dapat diputus tanpa konsekuensi tragis. Kita telah melihat konsekuensi itu minggu ini. Kita akan melihatnya lagi, di tempat lain, dengan skala yang lebih menghancurkan, jika negara tidak bertobat secara struktural.
Aceh-Sumut-Sumbar bukan akhir. Mereka hanya pengantar. Giliran daerah lain akan tiba bila oligarki tetap diberi mandat untuk menentukan masa depan bumi dan rakyat. Dan ketika air kembali naik, kita tidak bisa lagi berkata bahwa kita tidak pernah diperingatkan.