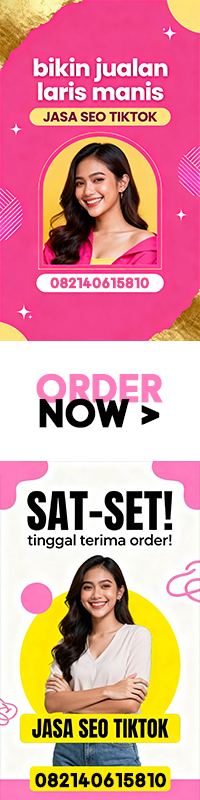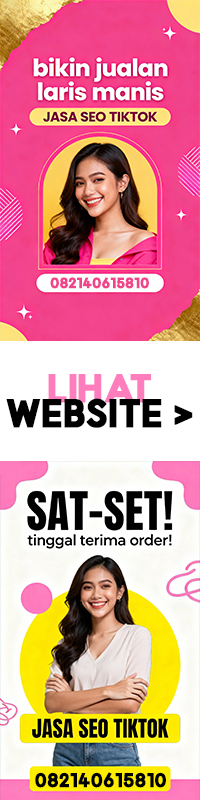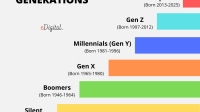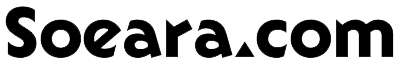Coba bayangkan sejenak, Indonesia tumbuh dengan Yogyakarta sebagai pusat pemerintahan. Kota yang akrab dengan suasana santai dan budaya halus itu mungkin memberi warna berbeda bagi perjalanan bangsa. Dalam sejarah, Yogyakarta tidak sekadar kota pelajar atau tujuan wisata budaya, tetapi juga ruang perjuangan bagi republik muda. Sejarawan Kuntowijoyo dalam Pengantar Ilmu Sejarah tahun 2013 menjelaskan bahwa Yogyakarta sejak lama dikenal sebagai pusat kekuatan moral. Kota ini menjadi tempat banyak gagasan lahir pada masa penuh harapan.
Salah satu momen paling mengesankan terjadi ketika Sri Sultan Hamengku Buwono IX memberikan dukungan finansial besar untuk republik. Beliau menyumbang 6,5 juta gulden, jumlah sangat besar pada masa ketika negara baru berdiri. Peter Carey dalam Biografi Politik Sultan Hamengku Buwono IX tahun 2019 mencatat bahwa bantuan itu membuat pemerintahan tetap berjalan. Setelah itu, Sultan berkata bahwa Yogyakarta sudah tidak memiliki apa pun. Beliau meminta pemerintahan dipindahkan ke Jakarta agar roda negara terus berputar.

Dari titik ini, imajinasi sejarah mulai bergerak. Bagaimana jika Sultan tidak mengucapkan kalimat itu. Bagaimana jika pemerintah tetap bertahan di Yogyakarta dan menjadikannya ibu kota permanen. Pertanyaan itu menarik karena pusat pemerintahan memengaruhi arah pembangunan. Anthony Giddens dalam The Nation State and Violence tahun 1985 menulis bahwa ibu kota membentuk identitas negara. Artinya, tempat tinggal para pemimpin menentukan gaya kebijakan dan pola pembangunan.
Fenomena pembangunan Indonesia modern menunjukkan betapa kuatnya pengaruh Jakarta. BPS tahun 2023 mencatat bahwa Jabodetabek menampung lebih dari dua puluh delapan juta penduduk. Pertumbuhan luar biasa ini menciptakan polusi, kemacetan, dan banjir berkepanjangan. Jika ibu kota tetap di Yogyakarta, tekanan urbanisasi mungkin menyebar ke wilayah tengah. Pembangunan mungkin tidak menumpuk di kawasan barat Pulau Jawa saja. Kota-kota lain bisa tumbuh lebih seimbang.
Masalah lahir dari sentralisasi pembangunan yang panjang. Pemerintah banyak memusatkan kegiatan ekonomi di Jakarta sejak 1970an. Richard Bird dalam Intergovernmental Finance in Developing Countries tahun 2016 menyebut bahwa sentralisasi memicu ketimpangan. Aktivitas ekonomi bertumpuk pada satu titik dan menarik migrasi besar. Sementara itu, Yogyakarta memiliki tradisi tata ruang yang lebih terukur. Jika ibu kota ada di sini, pola mobilitas mungkin lebih lembut.

Untuk memahami arti penting sebuah ibu kota, kita perlu melihat definisinya. John Friedman dalam “World City Formation” tahun 1986 menyatakan bahwa ibu kota memiliki fungsi simbolik, administratif, dan ideologis. Dalam konteks ini, Yogyakarta sebenarnya memenuhi ketiganya. Kota itu memiliki nilai budaya kuat, struktur pemerintahan khas, dan sejarah perlawanan terhadap penjajahan. Jika ibu kota menetap di sana, karakter pemerintahan mungkin lebih dekat dengan rakyat.
Yogyakarta memiliki tata ruang yang berbeda dari Jakarta. Jalan-jalan lebarnya tidak ekstrem dan bangunan-bangunannya lebih rendah. Jan Gehl dalam Cities for People tahun 2010 menyebut bahwa kota berskala manusia lebih nyaman bagi warganya. Jika pemerintah membangun pusat administratif di Yogyakarta, mungkin mereka akan merancang kota yang menghargai ruang publik. Ibu kota bisa tumbuh dengan prinsip kenyamanan, bukan sekadar kecepatan.
Yogyakarta juga lekat dengan local genius atau kebijaksanaan lokal. Clifford Geertz dalam The Interpretation of Cultures tahun 1973 menjelaskan bahwa budaya dapat menjadi fondasi pemerintahan yang kuat. Kesultanan Yogyakarta sudah lama mempraktikkan kepemimpinan berbasis tradisi dan harmoni sosial. Jika pola itu diadopsi secara nasional, gaya politik Indonesia mungkin lebih lembut dan kolaboratif.

Keunikan lain muncul dari dominasi sektor pendidikan di Yogyakarta. Data Kementerian Pendidikan tahun 2024 menunjukkan bahwa kota ini memiliki rasio mahasiswa tertinggi dibanding jumlah penduduk. Jika pusat pemerintahan berada di kota pelajar ini, mungkin Indonesia berkembang menjadi negara yang bertumpu pada kreativitas. Keputusan nasional bisa lebih dipengaruhi oleh riset, diskusi terbuka, dan pertumbuhan intelektual.
Selain itu, keberadaan kerajaan—yang tetap berfungsi secara adat—memberi warna unik pada politik. Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah contoh pemimpin yang memadukan tradisi dan modernitas. Benedict Anderson dalam Imagined Communities tahun 2006 menulis bahwa simbol tradisi bisa memperkuat identitas nasional. Jika pusat simbolik itu berada di Yogyakarta, kita mungkin memiliki identitas kolektif yang lebih kuat.
Tentu muncul tantangan realistis. Yogyakarta memiliki wilayah lebih kecil dibanding Jakarta. World Bank dalam “Urban Development in Southeast Asia” tahun 2022 mencatat bahwa kota kecil memerlukan strategi tata ruang ketat jika menjadi ibu kota. Tantangan itu sebenarnya dapat diatasi dengan inovasi. Indonesia bisa mengembangkan kota bertingkat, sistem transportasi cerdas, dan pusat administratif yang efisien. Yogyakarta bisa menjadi kota mungil, tetapi tertata rapi.