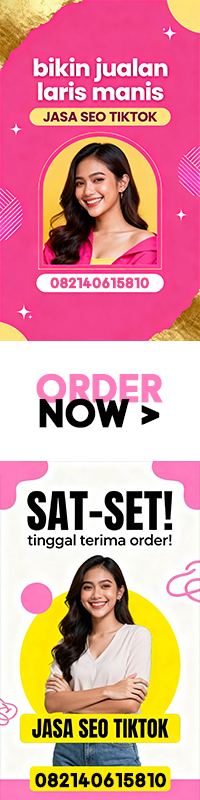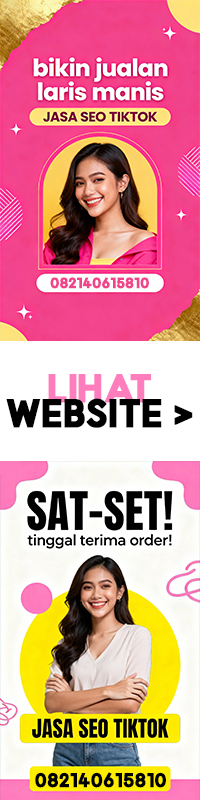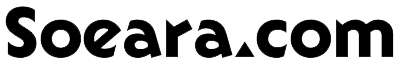Kebijakan Anggaran yang Tidak Selaras dengan Kebutuhan Masyarakat
Pengelolaan anggaran di Jawa Barat belakangan ini menunjukkan paradoks yang semakin sulit untuk disembunyikan. Di satu sisi, pemerintah provinsi menyuarakan efisiensi fiskal, pengendalian belanja, dan disiplin anggaran. Namun pada saat yang sama, berbagai OPD mengeluhkan pemangkasan anggaran yang justru menekan fungsi-fungsi pelayanan dasar. Ketidaksesuaian antara retorika efisiensi dan praktik yang terjadi di lapangan semakin mencuat ketika proyek renovasi fisik di kawasan Gedung Sate, mulai dari penataan halaman hingga pembangunan gapura senilai hampir Rp4 miliar, tetap berjalan mulus, bahkan dimasukkan dalam APBD Perubahan.
Kontras ini bukan sekadar teknis. Ia adalah cermin dari problem klasik dalam priority-setting pemerintahan, yakni adanya tarik-menarik antara kebutuhan publik yang substantif dan kebutuhan simbolik yang mudah dipertontonkan. Secara teoretik, kondisi ini menunjukkan bias dalam allocative efficiency sebagaimana dibahas dalam teori keuangan publik oleh Musgrave (1959) dan ekonomi kesejahteraan oleh Arrow (1963), yaitu ketika pemerintah gagal mengarahkan sumber daya ke sektor yang memberikan manfaat sosial terbesar. Ketika program pendidikan, kesehatan, sampai peningkatan kapasitas aparatur dipangkas, sementara infrastruktur simbolik ditingkatkan, maka pesan politiknya menjadi jelas bahwa estetika kelembagaan lebih diprioritaskan dari pada kualitas layanan publik.
Christopher Hood (1995) menyebut fenomena ini sebagai orientasi pada visible goods, yaitu proyek yang dapat dilihat, difoto, dirayakan, dan dikapitalisasi secara politik. Proyek seperti gapura baru dan halaman megah akan tampak lebih “nyata” bagi institusi, meski kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat tipis. Sebaliknya, program layanan publik yang intangible, seperti: perbaikan kapasitas SDM, layanan dasar, konsolidasi sistem tata kelola, sering kali dipangkas karena tidak memberi nilai simbolik yang mudah dipromosikan.
Kepanikan di Akhir Tahun Anggaran
Di ujung tahun anggaran, nampaknya wajah lain birokrasi kembali muncul, yakni ada kepanikan serap. Dalam banyak instansi, orientasi kinerja berubah menjadi perlombaan menghabiskan anggaran, bukan memastikan manfaatnya. Di titik ini, birokrasi terjebak dalam goal displacement, yaitu tujuan substantif pelayanan publik digeser oleh tujuan administratif semata berupa serapan tinggi, laporan keuangan rapi, dan SiLPA kecil.
Ironisnya, efisiensi fiskal yang digembar-gemborkan di awal tahun justru berubah menjadi manuver percepatan belanja di penghujung tahun. Ini bukan efisiensi, ini adalah bounded rationality ala Herbert Simon. Pemerintah mengambil keputusan yang “cukup baik untuk bertahan”, bukan yang optimal bagi masyarakat.
Krisis ini bukan hanya teknis. Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ia adalah masalah desain dan disiplin implementasi kebijakan. Ketika belanja ditahan tanpa strategi, lalu dibuka besar-besaran menjelang akhir tahun, seluruh siklus kebijakan berubah menjadi ritual fiskal yang miskin orientasi nilai publik.
Pertanyaan yang Menggema
Tidak mengherankan jika publik kemudian bertanya, sesungguhnya untuk siapa semua angka serapan itu dikejar? Apakah masyarakat merasakan manfaat dari pembangunan yang dikebut menjelang tutup buku? Atau hanya merasakan kemacetan, proyek tambal-sulam, dan kebijakan yang tidak mengakar pada kebutuhan mereka?
Kematangan kebijakan publik tampak dari konsistensi antara visi, alokasi sumber daya, dan implementasi. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan “Gedung Sate Bebas Polusi” dan “mempercantik Gedung Sate”, dengan adanya penataan halaman parkir dan pembangunan gapura adalah gagasan baik pada tingkat retorika. Tetapi ketika tidak disertai rekayasa lalu lintas dan penataan ruang yang matang, dampaknya justru menciptakan policy externalities, yakni kemacetan baru, beban bagi warga sekitar, dan ironi atas kebijakan yang seharusnya memperbaiki, bukan memperburuk kondisi lingkungan.
Simbolisme vs. Substansi
Fenomena ini menggambarkan problem besar tata kelola kita, yakni simbolisme lebih kuat daripada substansi. Gedung Sate diperindah, tetapi OPD kesulitan menjalankan layanan. Gapura megah dibangun, tetapi kapasitas pelayanan publik melemah. Lingkungan kantor dibangun ulang, tetapi ekosistem pelayanan masyarakat tidak tersentuh.
Jika pola ini terus berlanjut, Jawa Barat bukan hanya menghadapi persoalan teknis anggaran, tetapi juga persoalan legitimasi. Pemerintah daerah dapat kehilangan kepercayaan publik ketika alokasi belanja tidak relevan dengan kebutuhan riil masyarakat. Terlebih, pembangunan jangka panjang terancam stagnan ketika fiskal dihabiskan untuk estetika simbolik ketimbang investasi pada struktur layanan publik yang kokoh.
Kesimpulan
Sudah saatnya pemerintah melakukan lompatan paradigma. Anggaran bukan tujuan, melainkan alat. Serapan bukan prestasi, melainkan indikator administratif. Dan proyek simbolik bukan substansi pelayanan publik. Prestasi birokrasi bukan ketika anggaran habis, tetapi ketika masyarakat merasakan perubahan. Selama paradigma ini tidak bergeser, kita akan terus terjebak dalam lingkaran ritus tahunan yang tidak bermakna: panik serap, lupa manfaat.
Kini publik menunggu satu hal penting, yakni keberanian pemerintah untuk kembali pada esensi, bukan simbol. Pada manfaat, bukan angka. Pada pelayanan, bukan pencitraan. Hanya dengan itu anggaran publik dapat kembali menjadi instrumen kesejahteraan, bukan sekadar ornamen administratif dalam panggung politik daerah.