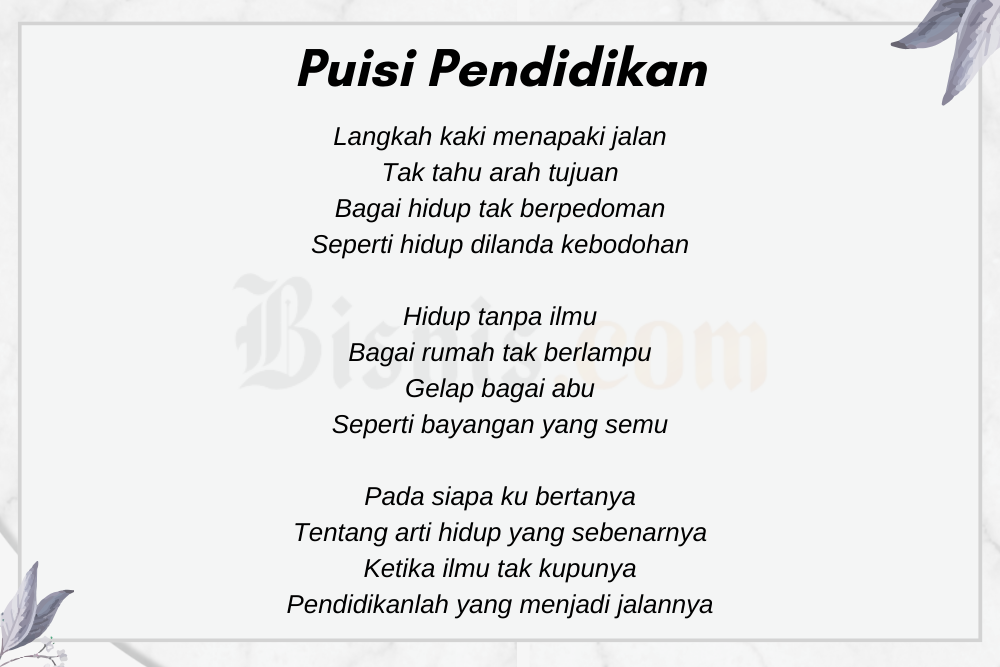Cerita Kehilangan dan Air Mata Gubernur Aceh
Di balik kata-kata yang penuh makna, terdapat cerita yang menyentuh hati. Seorang gubernur Aceh meneteskan air mata saat menceritakan empat kampung yang hilang akibat banjir besar pada November 2025. Dalam puisi yang disampaikan, ia menggambarkan kehilangan dengan indah dan menyentuh.
“Baru dua hari ia menjauh dari Aceh,
namun ketika menoleh, kampungnya telah tiada,
seperti halaman kitab yang dirampas langit
tanpa sempat meninggalkan serpihan tinta.”
Puisi ini menggambarkan perasaan Zainal, seorang ayah yang kehilangan rumah dan keluarganya. Pesan singkat tentang banjir besar menjadi penghancur dunianya. Bayang-bayang keluarga yang menyala seperti lampu yang menahan napas di ujung padam, menjadi simbol kekecewaan dan kehilangan.
Pertanyaan kecil Lala dulu hanya terdengar seperti rasa ingin tahu, kini berubah menjadi nubuat yang menggigil: “Ayah, kalau hujan keras, Lala sembunyi di mana?” Jawaban itu kembali menghantam dadanya: “Di dada Ayah, sayang… selalu di dada Ayah.”
Anggukan Lala menjadi doa kecil yang ia simpan seperti bunga di antara halaman langit. Namun Zainal tak sadar, janji itu tumbuh menjadi sesuatu yang tak sempat ia jaga.
Kehilangan Empat Kampung
Saat roda pesawat menyentuh bumi, bumi lain justru hilang dari hidupnya: Sawang lenyap. Jambo Aye lenyap. Peusangan lenyap. Empat kampung disapu arus, menjadi huruf-huruf basah yang dihapus sungai sebelum sempat dibaca sejarah.
Zainal memaksa pulang. Namun jalan ke Sawang sudah tiada. Yang tersisa hanyalah parut bumi yang terbelah seperti mulut raksasa, menelan masa lalu tanpa sisa. Ia berdiri di tepi jurang, berteriak sekencang mungkin: “Lala! Ayah pulang!” Teriakannya menanduk langit, retak menjadi serpihan gema yang hanya didengar awan, awan yang hari itu pun sedang belajar menangis.
Zainal terjatuh ke dalam dirinya sendiri; nama Tuhan berputar di dadanya seperti layang-layang putus benang, menyentuh langit sebentar, lalu jatuh kembali ke lumpur, serak napas yang tak sanggup menyebut apa pun.
Tanda-Tanda Kehilangan
Di antara lumpur yang menelan nama manusia, sebuah sandal ungu mengapung. Sandal kecil itu tampak ringan, namun bagi Zainal rasanya seberat seisi Aceh. Lala punya sandal seperti itu. Dan ia bertanya dalam hati yang retaknya tak sanggup ia sembunyikan: apakah itu sandal Lala?
Di tengah duka itu, ia teringat dirinya yang muda: aktivis yang pernah berteriak menolak hutan Sawang ditebang, hutan yang kini, seperti dirinya, kalah oleh dunia yang tumbuh tanpa jiwa.
Di hulu, para penebang menumpuk batang pohon seperti kitab suci yang kehilangan ayat; setiap gergaji yang bergerak menghapus satu doa hujan, mengirim banjir sebagai khotbah terakhir bumi yang letih. Dulu pohon-pohon itu berdiri sebagai penjaga kampung, menulis doa dengan akar. Kini mereka mengapung sebagai mayat panjang, membawa pesan: “Kami tumbang dulu. Kini giliran kalian merasakan sunyi kami.”
Perjalanan Menuju Paris
Alam tak membalas dengan amarah, melainkan dengan kearifan yang tak pernah meleset: yang digergaji akan balas menggergaji, yang ditebang akan kembali dalam bentuk banjir yang tak mengenal belas kasih.
Di dalam kepalanya, potongan sejarah berputar menjadi kaca patri yang pecah: letup senjata, serak sirene, janji penghijauan yang menggantung di lampu hotel, garis tinta yang merobek peta konsesi. Semua pecahan itu memantulkan satu kata yang bahkan tak sanggup ia bisikkan kepada dirinya sendiri: pulang.
Di kepalanya malam pecah seperti bendungan tua; nama Lala, deru gergaji, dan sirene kamp pengungsian bertabrakan, jadi satu arus gelap yang menyeret seluruh peta Aceh ke dalam dadanya.
Malam itu, di antara puing dan doa yang patah, Zainal berlutut. Ia menggenggam sandal ungu itu seperti menggenggam sebuah planet kecil, dan ia merasakan retaknya di telapak tangannya. Di genggamannya, hutan dan Lala menjelma satu bayangan: rindang rambut putrinya serupa rimbun daun yang pernah meneduhkan kampung.
Ketika batang-batang tumbang tanpa doa, baru ia paham, setiap pohon yang roboh adalah helai napas Lala yang diam-diam dipatahkan. Dan kampungnya di Aceh, yang malam itu entah di mana hilangnya, berubah menjadi air mata dan air bah, bersuara melalui angin: “Ingatlah aku. Rawatlah aku. Sebelum aku kembali hanya sebagai kenangan.”***
Menuju Paris, di atas pesawat, 3 Desember 2025